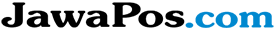 Bantul - Batu bertumpuk alias seni menyusun batu atau rock balancing art sempat menghebohkan Indonesia dalam dua bulan terakhir. Namun, sebenarnya dari mana seni menyusun tumpukan batu ini bermula?
Bantul - Batu bertumpuk alias seni menyusun batu atau rock balancing art sempat menghebohkan Indonesia dalam dua bulan terakhir. Namun, sebenarnya dari mana seni menyusun tumpukan batu ini bermula?
Menurut pendiri Komunitas Balancing Art Indonesia, Suryadi, seni batu bertumpuk sebenarnya sudah ada sejak zaman baheula.
Advertisement
Baca Juga
"Namanya susun batu. Sejak zaman dulu di Indonesia sudah ada," ucap warga Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu, kepada JawaPos.com, Minggu, 4 Maret 2018.
Salah satu bukti dari seni itu adalah sebuah mahakarya berupa Candi Prambanan yang terletak di Kabupaten Sleman, DIY. Keberadaan candi itu merupakan simbol yang paling nyata dari seni menyusun batu atau batu bertumpuk.
"Candi itu simbol interlock yang paling besar," katanya.
Baca berita menarik dari JawaPos.com lain di sini.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Batu Bertumpuk dan Filosofinya
Di zaman modern, seni menyusun batu dikenalkan oleh Michel Grab di Italia, sekitar dekade 90-an. Lalu menyebar ke negara-negara Asia, seperti Jepang, Tiongkok, kemudian Indonesia.
Di Indonesia sendiri saat ini baru menjadi heboh. Setelah adanya kejadian di Jawa Barat, muncul fenomena banyaknya tumpukan batu yang ada di sungai. Tepatnya di aliran Sungai Cibojong, Desa Jayabakti, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, awal Februari lalu.
Lantaran menarik perhatian masyarakat di sana, aparat setempat sempat meruntuhkan tumpukan batu di sungai tersebut. Namun, kabarnya saat ini sudah mulai digarap dalam bentuk wisata. "Ini juga sebagai bentuk kampanye untuk kelestarian lingkungan juga," ujar Suryadi.
Menurutnya, ada filosofi dalam art balancing tersebut. Pasalnya dalam penyusunan batu-batu tersebut, memerlukan konsentrasi yang maksimal, tingkat kesabaran, dan kepekaan tinggi. Untuk menemukan zero point atau titik antara ujung batu dengan batu lain yang ditumpuk.
Mood dari seorang balancer pun harus pada saat yang nyaman, dan ikhlas seperti seseorang yang sedang melakukan meditasi. "Unsur, pernapasan, kesabaran, emosional kontrol, itu dasar yang kuat," katanya.
Setelah melalui tahapan proses itu, seorang balancer pun dari sisi teknisnya akan semakin terasah. Ia tak lagi memikirkan hasil dari pembuatan seni balancing art, melainkan lebih menikmati setiap langkah yang dilakukan.
Ia mencontohkan pada pengalamannya sekitar 2013 lalu. Ketika itu, ia sendirian di sebuah sungai, membuat rock balancing.
"Saya dikira orang gila, mainan baru di sungai. Lagi mau ambil kamera, ada orang lempar batu (di rock balancing). Ya runtuh semua to. Pas balik lagi di sana, sudah runtuh. Aduh mau foto apa ini. Dari situ saya tahu emosional kontrolnya harus bagaimana," tuturnya.
Advertisement
Sering Dianggap Bukan Seni, tapi Mainan
Suryadi merasa memang tidak semua orang menerima bahwa batu bertumpuk sebuah seni dan dianggap mainan. Ia pun perlahan kembali memulai membuatnya lagi dari nol, dan kemudian difoto.
"Saya foto dari berbagai angle. Ngopo nesu (ngapain ngambek sama orang yang lempar batu). Misal ada orang saya marah-marahi karena belum bisa baca, apa bijak," tuturnya.
Apalagi, setiap orang mempunyai keterbatasan. Pemahaman yang belum dimengerti, lebih baik ia mencoba memberikan edukasi dengan cara membuktikan kalau itu sebuah seni. "Setelah tahu kalau saya asyik foto-foto, akhirnya orang itu paham kalau itu sebuah seni," ucapnya.
Filosofi lainnya dari gravity itu, lanjut pria yang juga merupakan seorang abdi dalem Keraton Yogyakarta tersebut, rock balancing terbentuk dari 2 garis antara vertikal dan horizontal. "Vertikal menggambarkan antara manusia dengan Tuhannya," katanya.
Sedangkan horizontal antara alam semesta dengan manusia itu sendiri. "Dari atas ke bawah (manusia) itu nol. Begitupun secara horizontal, manusia itu nol, zero point-nya itu. Kita itu nol. Sehebat apa pun manusia, harus introspeksi diri jangan sombong. Menemukan sikap sederhana," pungkasnya.

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1635463/original/067897900_1498712467-Obama-Kunjungi-Candi-Prambanan-6.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1965844/original/037487700_1520316469-20180306-rock_balancing-pendiri_balancing_indonesia-bantul.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1859808/original/051417100_1517592583-WhatsApp_Image_2018-02-02_at_17.21.15.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5188791/original/023453700_1744710488-WhatsApp_Image_2025-04-14_at_14.29.25.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5182015/original/054499600_1744021083-1.jpg)

:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/818/original/054214200_1562904925-anrijas1.JPG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/avatars/360649/original/076094300_1521185970-hmb_komo.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196927/original/007085500_1745463041-491894543_18357587902183597_8422628110937128470_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4922636/original/018407700_1724099535-IMG-20240820-WA0000.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3055800/original/096359100_1582183450-WhatsApp_Image_2020-02-20_at_1.55.36_PM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5197095/original/095472700_1745465951-GRIB_Bantah_Pelaku_Pembakaran_Mobil_Anggotanya_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5197095/original/095472700_1745465951-GRIB_Bantah_Pelaku_Pembakaran_Mobil_Anggotanya_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5197088/original/050634000_1745465603-Diancam_Dibunuh__Dedi_Mulyadi_Sudah_Biasa....jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5197088/original/050634000_1745465603-Diancam_Dibunuh__Dedi_Mulyadi_Sudah_Biasa....jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196990/original/035274800_1745464101-MBG_Batal__Ratusan_Siswa_di_Sukabumi_Kecewa.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196990/original/035274800_1745464101-MBG_Batal__Ratusan_Siswa_di_Sukabumi_Kecewa.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196147/original/054229000_1745394680-1280x720__5_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196147/original/054229000_1745394680-1280x720__5_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196182/original/086390800_1745395656-Dedi_Mulyadi_Tegaskan_Bakal_Memberantas_Premanisme_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196182/original/086390800_1745395656-Dedi_Mulyadi_Tegaskan_Bakal_Memberantas_Premanisme_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196642/original/060391600_1745439369-yem_3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4010148/original/039059400_1651147560-magetan_banget.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4011534/original/006410100_1651253252-033803600_1651147560-Merdeka_Dede_Bondan_magetanbanget.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4596421/original/083755500_1696307881-a.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5156255/original/046591400_1741439366-Screenshot_2025-03-08_200714.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4596607/original/049205400_1696316745-Gunung_Lawu_Terbakar__Begini_Kondisi_Warung_Tertinggi_se-Indonesia.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5195274/original/002034300_1745336208-Untitled.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3099740/original/069779200_1586667753-20200412-Misa-Malam-Paskah-9.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5187861/original/067378300_1744688801-Pengusaha_yang_Tahan_Ijazah_Datangi_Rumah_Wakil_Wali_Kota_Surabaya.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5195063/original/086249200_1745318388-20250422-Jenazah_Paus-AFP_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/thumbnails/5196444/original/099186600_1745405851-misa-arwah-untuk-paus-fransiskus-liputan-6-697a69.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5136452/original/056970900_1739861239-IMG_9781.JPEG)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5093522/original/015938400_1736834531-Snapinsta.app_473026451_947857726937425_5034596528200514747_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5182407/original/075453800_1744086847-20250408-PNS_Balkot-HER_3.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196788/original/052887200_1745458002-model_abaya_arab_hitam_terbaru_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2358749/original/070880200_1536904477-afpprison.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5047965/original/019798400_1734006795-Depositphotos_383353723_L.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5171207/original/055514200_1742621018-20241218_140323.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2824685/original/021647400_1560132686-61412080_809270982789977_4990936105040107271_n.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5148309/original/093801700_1740981558-Snapinst.app_482068629_18490845919030499_8053469952725536743_n_1080.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5197173/original/037813300_1745467460-Best_moments_of_the_game_Final_Four_vs_Surabaya_Samator___JakartaLavAniLivinTransmedia_LavAniForever.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5197249/original/091008800_1745469065-20250424-Israel_Serang_Sekolah_di_Gaza-AFP_1.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196883/original/059950400_1745462271-WhatsApp_Image_2025-04-24_at_9.33.59_AM.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4330290/original/075300500_1676880037-daniel-romero-yl5mP6gcPoc-unsplash.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4721215/original/050847100_1705711212-fotor-ai-2024012073921.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3172729/original/052282800_1594117386-20200707-Harga-Emas-Pegadaian-Naik-Rp-4.000-4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4723185/original/051536300_1705921815-fotor-ai-2024012218929.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5186929/original/033423400_1744629097-20250414-Harga_Emas_Batangan-AFP_2.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3149802/original/071712000_1591853665-20200611-Harga-Emas-Antam-Naik-ANGGA-4.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196267/original/018261200_1745398437-ATK_BOLANET_Brand_Tap_In_BRI_Liga_1_2024_Exclusive.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5195917/original/084098300_1745387064-IMG-20250419-WA0003.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5196167/original/011061400_1745395271-BRI_Liga_1_2024_25_Schedule_ATK_Bolanet_Matchweek_30__1_.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5195761/original/022584900_1745383030-ATK_Bolanet_BRI_Liga_1_2024_BIG_MATCH.jpg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5195108/original/009406800_1745321807-IMG_0933.jpeg)
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/5194828/original/005123800_1745309325-BRI_Liga_1_2024_25_Schedule_ATK_Bolanet_Matchweek_30.jpg)